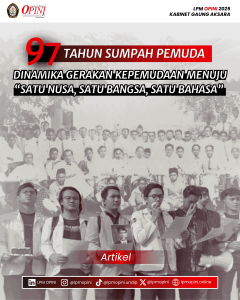97 TAHUN SUMPAH PEMUDA: DINAMIKA GERAKAN KEPEMUDAAN MENUJU “SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA”
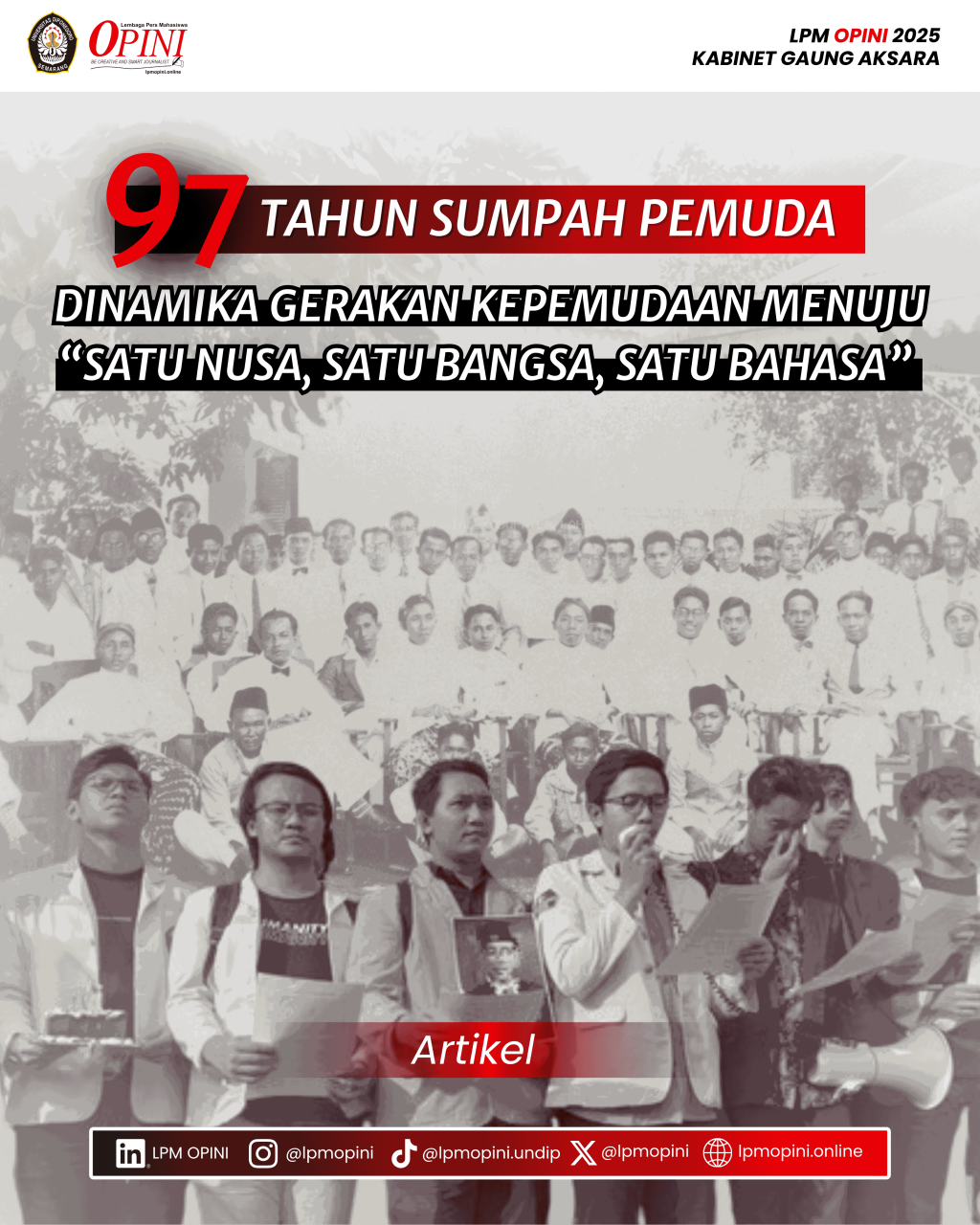
(Desain: Malya Zahraa’ni Gumilar, Izza Karimatan Fitria)
Pemuda dan Gerakannya
Gerakan kepemudaan di Indonesia, merajut lembaran kisah dari tiap era yang berbeda. Gerakan kepemudaan di masa kolonial, diilhami semangat melepaskan diri dari belenggu penindasan bangsa asing di Bumi Nusantara. Sementara gerakan-gerakan pemuda pasca kemerdekaan, terfokus namun tidak terbatas pada upaya kritis atas rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan rezim yang berkuasa.
Berbicara mengenai gerakan kepemudaan, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak membahas peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928, atau tepat 97 tahun yang lalu, sejumlah organisasi kepemudaan berhimpun pada Kongres Pemuda Kedua. Menghasilkan ikrar sakral, yang kemudian kekal abadi sebagai Ikrar Sumpah Pemuda. Akan tetapi, bagaimana sebenarnya dinamika gerakan kepemudaan di era tersebut hingga berhasil mewujudkan peristiwa Sumpah Pemuda?
Kongres Pemuda Pertama
Dalam sejarahnya, perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme yang lebih mengutamakan fanatisme kedaerahan selama tiga abad, memasuki sejarah baru dengan berdirinya sejumlah organisasi kepemudaan nasional. Perjuangan yang pada awalnya lebih bersifat kultural berubah menjadi perjuangan yang membawa isu-isu nasionalisme (Widodo: 2012).
Organisasi kepemudaan di Indonesia mulai bangkit di era 1920-an. Lahirnya organisasi pemuda seperti Tri Koro Darmo (Jong Java), Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Minahasa, hingga organisasi kepemudaan yang eksis di tanah Belanda yakni Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) menjadi tonggak gerakan kepemudaan di era kolonial.
Pada mulanya, organisasi-organisasi kepemudaan bergerak secara mandiri diakibatkan belum adanya suatu perhimpunan atau perkumpulan yang mampu menyatukan beragam elemen gerakan pemuda dengan latar belakang identitas berbeda tersebut. Akan tetapi, upaya untuk menghimpun seluruh organisasi kepemudaan terus diupayakan. Hingga pada 30 April – 2 Mei 1926, diselenggarakanlah Kongres Pemuda Pertama.
Rahman, dkk (2008) dalam bukunya bertajuk “Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional” menuliskan bahwa pada Kongres Pemuda Pertama, terdapat sejumlah tokoh nasional yang hadir dan berorasi dengan beragam tema dan sudut pandang. Tidak hanya berkenaan dengan muatan atau unsur persatuan pemuda, beberapa di antaranya mengambil sudut pandang tentang pentingnya emansipasi wanita dalam materi pidato yang mereka bawakan.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Kongres Pemuda Pertama, Soemarto, membawakan pidato dengan tajuk Gagasan Persatuan Indonesia. Sementara itu, Bahder Djohan yang diwakili Djamaloedin menyampaikan pidato bertajuk Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia, yang berfokus pada adanya persamaan hak antara wanita dan pria. Sementara itu, tokoh kenamaan lainnya yakni Muhammad Yamin, berorasi dengan membawakan tajuk Kemungkinan Perkembangan Bahasa-bahasa dan Kesusastraan Indonesia di Masa Mendatang. Dalam pandangan Muhammad Yamin, hanya ada dua bahasa yang dapat dijadikan bahasa persatuan, yakni bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Bahasa Jawa atas dasar jumlah penutur terbanyak, sementara bahasa Melayu didasari karena telah menjadi bahasa pergaulan.
Akan tetapi, Mohammad Tabrani selaku Ketua Kongres Pemuda Pertama tidak sependapat apabila bahasa persatuan dinamakan bahasa Melayu. Jalan pemikiran Mohammad Tabrani saat itu apabila nusa bernama Indonesia, bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus bernama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Ketidaksepahaman ini menjadikan Kongres Pemuda Pertama tidak menghasilkan keputusan kongres (Rahman, dkk: 2008).
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa
Kurang lebih 4 bulan pasca Kongres Pemuda Pertama, Partai Komunis Indonesia (PKI) pada September 1926, melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan tersebut berhasil diredam. Sebagai tindak lanjut dan upaya meminimalisir hal serupa, Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberlakukan kebijakan Vergader Verbond. Organisasi pemuda, atau partai-partai yang dianggap revolusioner dilarang untuk mengadakan pertemuan dengan melibatkan lebih dari tiga orang.
Akan tetapi, gerakan kepemudaan tidak luntur begitu saja dengan adanya kebijakan tersebut. Dalam perkembangannya, pada 20 Februari 1927, organisasi kepemudaan baru dengan nama Jong Indonesia yang kemudian berganti menjadi Pemoeda Indonesia, terbentuk. Pada mulanya, organisasi tersebut menghimpun pelajar dari sekolah menengah serta mahasiswa. Akan tetapi, kalangan mahasiswa kemudian mendirikan organisasinya sendiri dengan nama Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi kepemudaan lainnya kemudian terus bertumbuh dan bermunculan, salah satu di antaranya yakni Pemoeda Kaum Betawi.
Setelah dua tahun pasca Kongres Pemuda Pertama yang belum mencapai kesepakatan untuk menyatukan organisasi kepemudaan, pada 3 Mei dan 12 Agustus 1928, PPPI melaksanakan pertemuan guna membahas kongres berikutnya. Dalam perkembangannya, dibentuklah Panitia Kongres Pemuda Kedua yang kemudian menyepakati Kongres Pemuda Kedua akan dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda Kedua tersebut hadir sejumlah organisasi kepemudaan seperti PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamiten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, serta Pemoeda Kaum Betawi.
Sama seperti Kongres Pemuda Pertama, pada Kongres Pemuda Kedua, sejumlah tokoh turut menyampaikan orasinya. Muhammad Yamin dengan pidatonya bertajuk Persatuan dan Kesatuan, serta Inoe Martakoesoema yang menyatakan bahwa persatuan tidak bisa hanya sekadar dibicarakan namun harus ditanamkan dalam hati. Dalam keberjalanan kongres, sejumlah hambatan terjadi. Peserta kongres, oleh Pemerintah Hindia Belanda utamanya aparat keamanan, dilarang membawa perihal kemerdekaan serta politik selama kongres berlangsung.
Kongres tersebut setidaknya berlangsung dengan 3 kali rapat. Usai rapat ketiga, sebelum putusan kongres dibacakan, Wage Rudolf Soepratman sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, membawakan lagu sakral tersebut menggunakan biolanya. Kongres Pemuda Kedua pula menghasilkan ikrar ikonik yang hingga kini masih sering didengungkan dalam agenda peringatan Sumpah Pemuda.
“Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedua: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia,”
Pasca Kongres Pemuda Kedua, sejumlah organisasi kepemudaan menyatakan bersedia untuk fusi (menyatu). Di antaranya ialah Jong Java, Pemoeda Sumatera, Jong Celebes, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya.
Peristiwa Sumpah Pemuda, menjadi pengingat bahwa gerakan kepemudaan di Indonesia telah tumbuh sejak lama. Dengan segala dinamika yang terjadi di masa kolonial, para pemuda di era tersebut tetap berupaya kokoh berdiri guna menyatukan seluruh gerakan kepemudaan yang tersebar di sejumlah daerah. Melalui forum-forum pertemuan dan kongres, tepat pada 28 Oktober 1928, ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” resmi berkumandang, menjadi simbol persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia untuk bersatu padu, dalam menyongsong masa depan bangsa.
Referensi
Rahman, Abdul Momon,dkk. (2008). Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Museum Sumpah Pemuda
Widodo, Sutejo. (2012). Memaknai Sumpah Pemuda di Era Reformasi. E-Journal UNDIP.
Penulis: Muhammad Syauqi Al Sunni
Editor: Kayla Fauziah Fajri
Pemimpin Redaksi: Kayla Fauziah Fajri