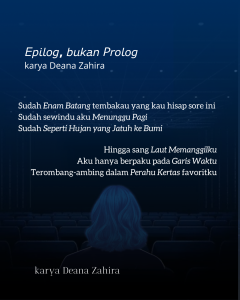Jangan Lupakan LGBTIQ di Perayaan Hari Perempuan Sedunia

Bendera pelangi sebagai simbol LGBTIQ di peringatan IWD 2022 Semarang (8/3). (Foto: Dinda Khansa)
LPM OPINI – Peringatan Hari Perempuan Sedunia masih terus bergaung jelang akhir Maret sejak dibunyikan gongnya per 8 Maret lalu dengan iringan kampanye #BreakTheBias. Perayaan tahunan yang jadi momentum kolektif pergerakan perempuan ini tidak lepas dari catatan kritis bahwa pesta ini bukan milik perempuan cis-gender saja, tetapi juga perempuan interseksional atau kelompok LGBTIQ.
Dukungan untuk LGBTIQ menjadi genting di tataran sistem heteronormatif yang ditandai rentetan peraturan diskriminatif oleh Pemerintah. Teranyar, pada tanggal 21 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan Walikota Bogor, Bima Arya, telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s).
Perilaku penyimpangan yang dimaksud dalam Perda ini adalah homoseksual, lesbian dan waria sebagaimana termaktub pada Bab III pasal 6. Secara ilmiah, Perda ini bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam PPDGJ III Kemenkes RI poin F66 disebutkan “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan”. Selain itu, International Classification of Diseases revisi ke-11 juga menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.
Maraknya tindakan nirmanusiawi terhadap kelompok LGBTIQ menjadi alasan besar mengapa panggung Hari Perempuan Sedunia juga layak menjadi panggung bagi LGBTIQ. Terlebih, identitas gender perempuan bukan hanya bisa diartikan dalam bentuk jenis kelamin, melainkan identitas dari individu masing-masing.
“Kalau berkaitan sama IWD, ketika bicara perempuan, kita mesti interseksional, karena dengan perspektif interseksional kita bisa lebih membaca kerentanan yang beragam,”
“Yang aku soroti di sini dari kelompok minoritas gender dan seksualitas, karena kadang ketika kita bicara perempuan kita lupa bicara soal LGBTIQ juga, karena di situ juga ada perempuan transgender (transpuan) atau waria, atau siapa pun teman-teman mengidentifikasikan dirinya, selama dia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan dia adalah perempuan,” tegas Himas Nur, salah satu peserta aksi saat diwawancarai pasca orasi pada perayaan Hari Perempuan Sedunia di Semarang, Selasa (8/3).
Menurut Himas, perjuangan atas nama perempuan masih kurang merangkul gender minoritas lainnya. Padahal, kesempatan untuk menyuarakan keresahan dari kelompok LGBTIQ sendiri terbilang sempit. Tidak banyak ruang-ruang aksi yang dapat dijadikan ajang bersuara kelompok minoritas gender karena begitu maskulinnya aksi-aksi yang berkaitan dengan politik kenegaraan di Indonesia.
“Ini yang kurang disuarakan, perempuan transgender, perempuan kelompok orientasi seksual minoritas, misal perempuan lesbian, perempuan biseksual, perempuan aseksual, perempuan panseksual, dan lain sebagainya. Menurutku ini penting juga IWD jadi ruang buat teman-teman kelompok gender dan seksualitas, karena di mana lagi kita LGBTIQ bisa punya ruang aman sendiri. Misalnya dalam demonstrasi saja masih maskulin, enggak mungkin kita misalnya demo Wadas sambil bawa bendera pelangi gitu, kan,” ucap Himas diakhiri tawa renyah.
Masalah yang dialami kelompok LGBTIQ tidak lepas dari stigma buruk terhadap kelompok gender nonbiner. Kuasa heteronormativitas yang berkembang di masyarakat menurut Himas juga diperparah oleh media. Pers yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi dan menyuarakan keadilan gender serta hak asasi manusia justru kerap membingkai LGBTIQ dalam pemberitaan yang diskriminatif dan bernada negatif.
“Budaya atau kuasa heteronormativitas ini kan suatu sistem kuasa yang melanggengkan bahwa hanya ada satu orientasi, itu diskriminatif dan represif; hanya ada laki-laki dan perempuan saja, atau kalau tidak hanya ada heteroseksual saja,”
“Belum lagi stigma dan framing media, kalau pelakunya gay, yang disorot gaynya, tapi kalo pelakunya cis-male, laki-laki, perempuan yang hetero, enggak ada di-highlight dengan identitas gender cis-gender perempuan atau laki laki. Jadi peran peran beberapa pihak juga perlu dibenahi,” kata Himas.
Mendorong RUU TPKS yang Ramah Gender dan Korban
Dalam orasinya, Himas berharap pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang berperspektif korban. Dengan begitu, setidaknya tercipta payung hukum yang secara perlahan bisa mendobrak stigma yang kerap dilabeli pada kelompok LGBTIQ, meskipun Himas mengiyakan bahwa perjalanan bahkan masih belum mampu membuka pintu gerbang.
“Kalau kemudian RUU TPKS bisa disahkan, harapannya payung hukumnya sudah ada, nih, meskipun implementasinya pasti masih butuh pekerjaan rumah yang banyak, pengesahan itu kan baru pintu gerbang, bukan jalan akhir,”
“Tapi misal udah ada payung hukumnya semoga jadi agak sedikit hancur stigmanya, karena masih banyak stigma LGBTIQ itu pelaku kekerasan seksual, karena yang perlu kita ketahui bareng-bareng, kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh siapa saja, enggak terbatas sama orientasi seksualnya dan identitas gendernya,” terangnya.
Terlalu banyak ranjau untuk hanya membuka sloof gerbang itu. Banyak pihak yang mengutuk RUU TPKS dengan dalih macam-macam; salah satunya menuduh RUU TPKS melegalkan zina dan LGBT. Padahal, menurut Himas, pernyataan seperti itu tidak masuk akal. Kondisi LGBTIQ yang telah direpresi berbagai aturan hukum di Indonesia justru adalah tanda bahwa LGBTIQ dikriminalisasi, amat berkebalikan dengan kata legalisasi.
Bagi Himas, RUU TPKS lebih tepat dianggap sebagai rancangan untuk memanusiakan manusia, sehingga semua manusia; terlepas dari apa pun identitas gender serta orientasi seksualnya, mampu mendapat perlindungan yang setara dari ancaman kekerasan seksual.
“Masih banyak stigma terhadap RUU TPKS kalau ngelegalin zina, LGBT, dan sebagainya, dilegalin gimana? Orang sudah dikriminalisasi juga. Enggak dilegalin, tapi ketika kita lebih bisa memanusiakan manusia dan RUU TPKS melindungi LGBTIQ dari kekerasan seksual yang dialami LGBTIQ,”
“Banyak teman-teman lesbian yang sengaja diperkosa sama keluarganya sendiri, biar “jadi” suka cowok, itu jahat banget, tapi enggak kecatat karena ada embel-embel lesbiannya dan atas nama terapi konversi yang sebenarnya dilarang. Yang perempuan cis-gender sudah susah dapet perhatian aparat apalagi lesbian atau kawan-kawan transpuan yang diperkosa biar jadi laki-laki,” pungkas Himas.
Sejak diusulkan Komnas Perempuan pada 2012, RUU TPKS (sebelumnya RUU PKS) sudah beberapa kali keluar-masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menginjak usia ke sepuluh, RUU ini telah mengalami pemangkasan definisi pelecehan seksual dari 15 jenis, lalu dipangkas menjadi 9 jenis, dan pada 2021 dipotong kembali menjadi 4 jenis pelecehan seksual sekaligus berubah nama menjadi RUU TPKS yang masuk Prolegnas 2022 dan diharapkan bisa segera disahkan.
Penulis: Luthfi Maulana
Editor: Almira Khairunnisa